SEPEDA
…
Laju sepeda kumbang di
jalan berlubang
S’lalu begitu sejak
zaman Jepang
…
Itu sepeda butut dikebut
lalu cabut
Kalangkabut sampai
kentut
…
Penggalan syair di atas
kukutip dari lagu gubahan Iwan Fals yang bertajuk “Umar Bakrie.”Lagu ini
menceritakan tentang seorang guru yang pegawai negeri. Ia hanya mempunyai upah kecil
sekali tapi masih pula gajinya dikebiri. Disunat. Dipotong.
Seorang guru yang setiap
harinya hanya mampu menggunakan sepeda. Ia hanya mampu bersepeda ke ‘ladang’
untuk menanam ‘benih-benih’ kecerdasan. Benih kecerdasan kepada para siswa
asuhannya. Anak-anak calon pemimpin bangsa.
Sebagaimana Umar
Bakrienya Iwan Fals, akupun demikian. Hanya bedanya ia pegawai negeri sementara
aku pegawai swasta. Ia pakai sepeda kumbang butut, aku pakai sepeda gunung.
Kereta angin mentereng.
Sepeda yang kunaiki
tidak butut. Tapi kalau semakin cepat kukayuh semakin kencang pula kernyitannya.
Bunyi-bunyi yang membising datang dari seluruh tubuhnya. Membuat semua orang
yang kulewati terganggu dengan kebisingannya.
Umar Bakrie memacu
sepedanya ngebut sampai
terkentut-kentut karena takut. Aku tidak sampai kentut. Kecuali kalau lagi
masuk angin dan mulas. Aku hanya menggelinding santai. Tak ada yang perlu
kutakuti. Aman!
Lagu ini menggambarkan
hidupku yang sesungguhnya. Setiap hari aku pergi pulang sekolah dan rumah naik
sepeda. Aku mengayuh sepeda memenuhi menghiasi jalan di kota modern. Dandananku
selalu tetap. Sama.
Topi menancap di kepala,
kaos plus jaket dan training spak
(celana) menutupi tubuh. Warna pakaianku tak jarang saling bertabrakan. Aku tak
menghiraukan. Sepatu kets serta ‘asesoris’ tas yang menyelempang menggelantung
menempel di punggung.
Aku mengayuh sepeda melalui
jalan-jalan setapak di kampung tempatku mengontrak rumah. Aku melintasi
jalan-jalan utama di jantung kota modern Tangerang, Banten. Berangkat pagi dan
pulang sore sambil bersiulkan nada-nada lagu Umar Bakrie.
Sekembali dari
‘perantauan’ selama tiga bulan di Kupang aku menganggur total. Demikian juga
istriku. Untuk kembali mengajar di sekolah yang dahulu, tak mungkin. Terlanjur
malu.
Jadilah kami berdua para
sarjana pengangguran dengan tanggungan dua jiwa lainnya. Untunglah rumah baru
terjual sepulangnya kami. Dengan uang hasil penjualan rumah itu kami bisa
bertahan hidup hingga aku mendapatkan pekerjaan di Tangerang, Banten.
Awalnya kami tinggal di
Bojong-Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Tetapi karena jarak tempuh antara
rumah dan sekolah tempatku mengajar terlalu jauh, aku pindah. Aku memboyong
keluargaku dari Bojong ke lokasi yang lebih dekat dengan ‘ladangku.’
Faktor utama yang
mendorongku untuk pindah alamat karena: Ongkos, waktu, dan tenaga. Semua faktor
itu cukup berpengaruh pada kesehatanku. Untunglah istriku bijaksana dan mau
mengerti.
Sudah dekat dengan
sekolah bukan berarti ekonomiku makin mantap dan berlebihan. Tidak. Justru
untuk pemulihan kondisi ekonomilah aku menggunakan sepeda. Satu-satunya
kendaraan termahal pemberian istriku dari uang hasil jual rumah.
Berharap dengan
mengendarai kereta angin ini ekonomiku kembali bangkit. Bisa kembali pulih.
Sehat seperti sedia kala. Aku Berusaha
menyisihkan sedikit demi sedikit setiap bulannya dari uang transporku. Darinya
aku dan keluarga kecilku bisa bertahan hidup.
Aku terpaksa harus
mengalahkan rasa maluku. Sekalipun harus melewati rumah-rumah mewah di kawasan
elit Modernland. Kawasan yang sebagian besar penghuninya adalah murid-muridku.
Kadang aku harus
membuang perasaan minder sekalipun beriring berdampingan dengan mereka. Beriringan
dengan mobil-mobil luks yang di
dalamnya ada murid-muridku. Dari sana ada satu atau lebih pasang mata sedang
menatapku.
Mata mereka dan/atau
orangtuanya mengikutiku dengan tatapan yang aneh. Tak jarang pula aku harus
mengebiri rasa dina dan papa ketika harus menstandarparkirkan sepedaku. Karena
sepedaku berada di antara ‘rimba’ mobil-mobil mahal. Mobil bermerek terkenal
milik anak-anak muridku. Apa boleh buat! The
show must go on!
“Pak, kenapa nggak pake motor?” Tanya salah seorang muridku suatu ketika sepulang
sekolah. Ia sedang menunggu mobil yang akan membawanya pulang. Kendaraannya
banyak. Ia sering berganti-ganti mobil. Terhenyak terhentak aku mendengar
pertanyaan itu.
Tapi dengan santai
kujawab: “Bapak bukannya nggak bisa
beli.” Belum selesai kalimatku ia sudah nyeletuk lagi: “Trus?” Lanjutnya tak sabar. “Nggak
punya uang.” Mendengar jawabanku itu ia diam. Mungkin bingung. Mungkin heran. Atau
tak percaya. Entahlah!
Yang jelas pembicaraan tentang sepeda tidak berlanjut. Berhenti terputus begitu saja. Kami pun akhirnya berpisah. Ia pulang dengan BMW. Aku juga. Maksudnya aku juga pulang dengan mengendarai sepeda reot.


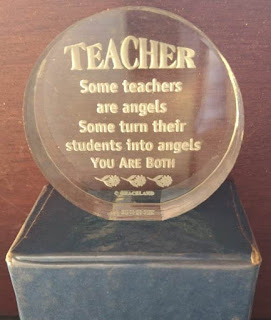
Kisah yang menarik dan penuh perjuangan,,,, satu keyakinan bahwa perjuangan dan kerja keras akan menghasilkan buah yang manis, apalagi disertai dengan rasa syukur Untuk apapun yang kita terima...
ReplyDeleteAmin! Terima kasih, Abang. Sudah mampir dan tinggalkan jejak. Gb!
ReplyDelete