MAU JADI GURU
Setelah lulus sekolah
menengah pertama aku mendaftar di sekolah guru olahraga negeri (SGON) Kupang. SGO
setingkat SMA atau SMU. SGO adalah tempat mencetak guru-guru yang siap mengajar
olahraga di jenjang sekolah dasar.
Ia merupakan evolusi
dari SGPD (sekolah guru pendidikan djasmani) lalu berubah nama menjadi SMOA
(sekolah menengah olahraga atas). Kemudian
menjelma menjadi SGO. Akhirnya tidak ada lagi seterusnya. Dihapus sama
sekali. Ia menghilang selamanya dari blantika dunia pendidikan Indonesia.
Tidak ada yang
menyarankanku untuk belajar di SGO. Apalagi memaksa. Itu sekolah satu-satunya
pilihanku. Aku memilih sekolah itu bukan karena cita-cita sejak kecil. Mungkin anak yang tidak punya cita-cita adalah
aku. Dan tak berani bercita-cita.
Kalau anak-anak ditanya
ingin jadi apa kalau sudah besar selalu ada jawaban. Mereka akan menjawab:
Dokter, insinyur, pilot, dan lain-lain. Aku tidak punya itu. Sekolah, ya,
sekolah saja tanpa berpikir mau menjadi apa kelak. Di benakku waktu itu sekolah
adalah kewajiban setiap anak. Titik.
Sekalipun tak punya
cita-cita aku tetap belajar dan rajin sekolah. Sekolah selanjutnya yang kupilih
adalah SGO lantaran nilai pelajaran Olahragaku lumayan tinggi. Dan memang aku
suka sekali berolahraga.
Hingga kini aku tetap
menyukainya. Aku menyukai olahraga karena profesi dan sebagai sarana juga
wahana berekspresi. Kata orang-orang pintar di layar-layar kaca: I feel free, when I am doing sport.
Begitulah perasaanku ketika lagi berolahraga.
Aku memilih masuk SGO
karena selain alasan suka pada olahraga juga gampang mendapat pekerjaan.
Setelah lulus bisa langsung mengajar walaupun hanya di jenjang sekolah dasar.
Dan tentunya cepat dapat penghasilan.
Kata orang Inggris: That was my simple frame of thinking at that
time. Tidak ada yang membimbing dan mengarahkan. Aku berpikir sendiri. Mengambil
keputusan sendiri. Dan melakukannya sendiri pula. Orangtuaku hanya mendukung
dalam hal dana bila memungkinkan.
Ada hal istimewa yang
aku dapat ketika belajar di SGO. Waktu itu aku berusia enambelas tahun. Itu
pertama kalinya ada rasa suka pada lawan jenis. Aku sungguh-sungguh ingin
mengenal lebih dalam tentang cewek.
Aku berusaha keras untuk
belajar berkomunikasi dengan anak cewek. Dan kalau bisa memenangkannya.
Maksudnya mendapatkan perhatiannya. Itu saja. Karenanya aku belajar dengan
melihat mengamati teman-teman saat mereka beraksi.
Adalah alamiah bila
seorang remaja mempunyai perasaan suka terhadap lawan jenisnya. Aku mengalami
itu ketika duduk di kelas dua SGO. Kelas sebelas sekarang. Perasaan itu datang
begitu saja. Aku tak membendungnya. Tapi tak juga membiarkannya meluap
sesukanya.
Aku justru mengontrolnya
dengan belajar lebih giat dan latihan lebih keras (mempertajam dan memperhalus
keterampilan dalam olahraga). Aneh memang. Tapi begitulah adanya. Itulah awal
aku tahu artinya suka dan jatuh cinta pada makhluk yang bernama perempuan.
Aku ingin napak tilas
sedikit. Memutar kembali untuk memperlihatkan kepada pembaca apa yang terjadi
dengan diriku di kelas satu. Kelas sepuluh. Di kelas satu atau sepuluh aku
duduk sebangku dengan Aloysius Kase.
Ia pernah menjabat
sebagai Wakil Kepala SD Abdi Siswa yang berlokasi di Taman Meruya Ilir Kebun
Jeruk, Jakarta Barat. Sekarang-sekarang ini ia sedang menekuni profesi baru
sebagai wiraswastawan. Sekedar berbagi informasi tentang temanku ini.
Aloysius dan aku
bertubuh kecil maka kami selalu duduk di barisan paling depan. Dekat dengan
meja guru dan papan tulis. Dengan demikian setiap guru yang mengajar di kelas
itu akan gampang menjangkau kami.
Suatu ketika kami
belajar bahasa Inggris. Jam pelajaran bahasa Inggris. Gurunya adalah istri
kepala sekolah. Ibu Didi, demikian kami mengenalnya. Orangnya humoris tapi
tegas. Berperawakan tinggi dan tegap.
Caranya mengajar enak
dan mudah dipahami. Kami semua menyukai dan menikmatinya dengan antusias. Hanya
aku yang tidak paham. Terlanjur jengkel semenjak di sekolah menengah pertama.
Guruku ini selalu
berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sekarang baru aku paham bahwa pengajaran
bahasa yang benar adalah yang demikian. Langsung menggunakan bahasa yang sedang
dipelajari. Apapun bahasanya. Itu aku dapati setelah mengeksplorasi buku-buku
bahasa, termasuk inggris.
Ibu Didi selalu
berbicara bahasa Inggris. Maksudnya agar telinga kami terbiasa mendengar
kata-kata bahasa itu. Selain aktif mendengar kami juga didorong untuk mengucapkannya.
Dengan metode itu ia
berharap kami semua dapat dengan lancar ber-cas
cis cus. Berbicara bahasanya Pangeran Charles tersebut. Kecuali kalau
menjelaskan tentang sesuatu konsep kebahasaan yang rumit, ia akan menggunakan
bahasa Indonesia.
Aku tak memiliki fondasi
yang baik dalam bahasa ini. Sekali lagi karena terlanjur terluka saat di
esempe. Maka setiap kali Ibu Didi, guruku itu mengucapkan kosa kata bahasa
Inggris, aku dan Aloy malah membahasnya dengan dan dalam bahasa Timor.
Perkenankan aku mengulas
sedikit hubungan bahasa Inggris dan bahasa Timor. Tepatnya Timor Dawan. Yang
Aloy dan aku otak atik seturut hati tergelitik. Begini!
Kosa kata bahasa Timor
memiliki kemiripan bunyi atau pengucapan dan penulisan dengan bahasa Inggris. Namun
pengertiannya bag utara dan selatan. Sangat jauh berbeda. Itu yang menggoda
kami untuk bereksperimen saat belajar bahasa Inggris.
Misalnya: Of artinya nanti dalam bahasa Timornya. Thank you bila diucapkan dengan aksen
bahasa Timor yang dimiringkan akan berbunyi sen
kiu, artinya menanam pohon asam. Please
bila diplesetkan akan berbunyi palis
artinya biarkan. Dan lain-lain.
Kawan, kami berdua
keasyikan mengata-katai kata-kata bahasa Inggris dengan kata-kata bahasa Timor.
Kata-kata yang kami ucapkan mempunyai pengertian yang lain dari yang dimaksud
oleh ibu. Kami pun tertawa. Kadang lucunya bersamaan dengan kata-kata yang
diucapkan oleh Ibu Didi.
Pada saat seluruh kelas
tertawa kami pun lucu. Kami terpingkal kegelian bukan karena lucu yang datang
dari kata-kata ibu guru. Tetapi akibat pembahasan kami berdua dalam bahasa
Timor. Kata anak zaman now: So far so good. Semuanya berjalan
baik-baik saja. Aman sentosa dunia dan akhirat.
Kebiasaan itu membuat
kami semakin menjadi-jadi. Kami terus mengotak-atik kata-kata bahasa Timor yang
menyebabkan kelucuan lokal (cuma kami berdua). Kebablasan. Kami tidak memperhatikan keterangan guru lagi. Yang
mestinya tidak lucu menurut ibu guru, justru kami tertawa.
Ia mulai curiga. Sekali,
dua kali masih dibiarkan. Ketiga kalinya ia sudah tak tahan. Maka tanpa
ekspresi marah ia menyentil hidung kami, aku dan Aloy. Hanya satu kali. Tapi
cukup keras. Demikian kerasnya sehingga menyebabkan gelembung bening bergulir
dari bola mataku. Bukan menangis. Rasanya seperti mau bersin yang tertunda.
Mungkin beliau tidak
tega menampar atau menempeleng kami. Lalu dengan satu kalimat perintah ia
bilang: “Ke sana kamu, tikus-tikus kecil” Ia menunjuk ke luar. Ke arah lapangan
tempat kami biasa melaksanakan upacara bendera.
“Berdiri di tiang
bendera itu sampai pulang sekolah.” Dengan mulut terkancing rapat kami berdua
meninggalkan ruang kelas. Semua pasang mata mengikuti menghantar kami hingga
kami tiba di singgasana kesengsaraan.
Menyadari kelakuan kami
yang bejat itu, kami bersumpah untuk jangan pernah melakukannya lagi. Kami
berdua berjanji di terik matahari siang yang menusuk kulit. Janji ini disaksikan
pula oleh sebuah tiang yang di atasnya melambai elok sang merah putih. Kami berjabatan
sambil mengucapkan ikrar: “Kita harus menjadi yang terbaik.”
Sumpah itu bukan tong
kosong bohong melolong. Ikrar itu bagai pecut yang membuat kami berlari
kencang. Kami membuktikannya dengan kerja keras yang membuahkan. Kami naik kelas dengan predikat memuaskan.
Sekalipun bahasa Inggrisku hancur.
Aku naik kelas dua (sebelas)
dengan predikat peringkat satu. Terbaik dari seluruh siswa kelas satu (sepuluh)
yang berjumlah hampir seratus anak. Kami semua terbagi ke dalam dua kelas
paralel – A dan B.
Aku menjadi salah satu
sorotan (perhatian) dan dikenal oleh guru dan siswa dari semua jenjang. Itu
karena selain naik dengan predikat terbaik, juga karena di kelas dua (sebelas
itu) aku mulai aktif dalam setiap kegiatan sekolah.
Namun kawan, biarpun sebagai
seorang ‘public figure’ aku hanyalah
seorang siswa di sekolah. Sebagai siswa aku tidak kebal hukum. Hal apapun bisa
terjadi kapan saja atas diriku. Seperti ini. Aku mengalami satu kemalangan yang
memalukan yang hampir membuat namaku cacat.
Begini ceritanya!
Waktu itu adalah jam
pelajaran Fisiologi – Ilmu Faal. Ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian
tubuh manusia dalam keadaan normal. Diam. Gurunya adalah Drs. Marten Apono yang
biasa kami panggil Pak Ateng Apono.
Ia lulusan Sekolah
Tinggi Olahraga Jakarta. Entah tahun berapa. Beliau juga adalah mantan atlet
nasional dalam cabang olahraga tinju dan panahan. Jabatannya pada waktu itu
adalah wakil kepala sekolah.
Aku biasa dan selalu
duduk di barisan bangku paling depan. Tidak hanya untuk pelajaran ini. Tetapi untuk
semua mata pelajaran dan di jenjang atau kelas berapa pun. Itu aku lakukan
karena ukuran tubuhku kecil. Jadi aku harus duduk paling depan agar bisa
melihat dengan leluasa.
Namun hari itu aku
terserang sakit perut yang teramat sangat. Meskipun demikian aku tak mau
ketinggalan pelajaran karena pelajaran ini cukup sulit. Terlalu banyak kata
asing. “Pusssiiiing,” kata Pegy
Melatisukma salah seorang pesohor tanah air.
Oleh karena itu aku
memaksakan diri ikut. Aku menempati bangku paling belakang agar tidak
menimbulkan ekses yang tidak dikehendaki. Akibat sakit perut itu aku lemas
total. Pucat dan tak bertenaga.
Jam belajarnya di dua
jam pelajaran terakhir. Artinya selesai belajar Fisiologi, pulang. Selama
belajar semua berjalan lancar. Aman terkendali. Tidak ada kejadian yang
berdampak apapun. Kami menyelesaikan sesi ini dengan baik.
Tetapi ketika ketua
kelas mengajak kami semua berdiri untuk memberi salam ada yang ganjil. Ada yang
mengeluarkan kata-kata yang tidak biasanya. Entah apa? Aku sungguh-sungguh tak
konsentrasi lagi. Tak sanggup menahan rasa melilit.
Pak Ateng yang sudah
berada di bibir pintu, urung meneruskan langkahnya. Ia malah berbalik ke
mejanya dan meletakkan kembali buku-bukunya. Ia menghadap kami, lalu bertanya:
“Siapa itu?”
Intonasinya datar. Tidak
ada gejala marah. Semua diam. Bahkan tak ada yang bergerak. Masih dalam keadaan
terus berdiri. Ia bertanya untuk kedua kalinya.
“Siapa itu? Lebih baik
mengaku daripada saya marah.” Masih diam. Tak ada jawaban. Hanya masing-masing
pasang mata saling melirik.
Dalam keadaan lemas aku
melihat guruku membuka dan melepaskan jam yang dikenakan di pergelangan
tangannya. Ia lalu meletakkannya di atas meja. Ia menuju ke pintu dan
menutupnya sampai rapat. Kemudian kembali ke depan kami dan mengucapkan satu
ultimatum yang mengerikan.
“Kalau tidak ada yang
mengaku, maka kalian semua, satu per satu saya tampar sebelum meninggalkan
ruangan ini.” Ia mulai menggulung lengan bajunya. Suasana semakin tegang. Aku
pun semakin tidak karuan saking
menahan rasa melilit. Kondisiku tak menentu.
Tiba-tiba ada yang nyeletuk: “Yolis dan Michael, Pak!” Aku
terperanjat kaget. Suara itu datang dari berisan tengah. Kami berdua memang
sebangku. Michael Demonsili nama lengkapnya. Memang Michael terkenal konyol.
Suka membanyol yang membuat pendengarnya terpingkal. Tak terkecuali guru.
Aku sendiri siswa
berprestasi. Jadi mereka berbuat itu dengan suatu harapan siapa tahu Pak Ateng
tidak jadi marah. Semoga Pak Ateng bisa berbelas kasih dan mengampuni. Tapi apa
lacur, tak ada yang dapat mengubah keadaan.
Perlahan namun pasti. Ia
beranjak dari tempatnya berdiri menuju ke meja guru dan duduk di atasnya. Dari
sana ia menjulurkan tangan kanannya ke arah kami berdua. Telapak tangannya dihadapkan
ke atas. Ia menekukkan jari-jemarinya dan menggapai sambil memanggil.
“sini.” Suaranya
singkat. Pendek saja. Raut wajahnya yang keras bertambah kelihatan sangar.
Ditambah pula rambutnya yang kribo
dan kulitnya yang hitam semakin menunjang suasana seram. Tidak pilihan. Kami
beriring menyambanginya.
Dengan perasaan tak
menentu aku menghampirinya diikuti Michael. Sambil melangkah aku berdoa
singkat. Semoga aku dan Michael diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan. Pembelaan
diri.
Karena selama ini kutahu
bahwa beliau adalah orang yang sangat baik. Bijaksana. Ramah dan tidak pernah
mengumbar emosi dalam kondisi apapun. Demokratis. Ternyata semuanya di luar
dugaan.
Sebelum aku sampai di
hadapannya ia telah datang mendapatkan kami berdua. Dan, “plak.” Tangan kanannya menyangkut di pipi kiriku. Ujung daun
telingaku perih seketika.
Pandangan mata
kerlap-kerlip seperti kunang-kunang. Dunia terasa goyang. Benda-benda di
depanku kelihatan samar. Buram. Tidak jelas. Hanya bayang-bayang belaka. Aku
berusaha eling dan berdiri tegak yang
tak ajeg.
Tidak ada gerakan
pembelaan dariku. Ia maju selangkah meninggalkan aku dari sisi kiriku terus
menyongsong menghadang Michael. Langkah temanku ini terhenti dengan sebuah
bogem mentah.
Merasa diri besar,
tinggi, dan juga atlet silat, secara refleksif Michael menangkis dan mengelak.
Sebaliknya, karena pukulannya ditangkis emosi Pak Ateng semakin menjadi. Seru!
Kami bagai sedang menyaksikan sebuah pertandingan tinju.
Sebagai mantan petinju
yang terlatih baik, reflex dan naluri ‘membunuhnya’ terpancing. Awalnya cuma
tangan kiri. Akhirnya menjadi bergantian. Kanan-kiri, kanan-kiri. Terus sampai
Michael tak mampu lagi berbuat banyak. Menyerah. Pasrah. Dan, KO!
Kami yang menyaksikan
jadi merinding. Pak Ateng menyambar barang-barangnya yang ada di meja dan
melenggang meninggalkan ruangan tanpa sepatah katapun. Seisi kelas pulang
dengan perasaan dan pikirannya sendiri-sendiri.
Pada hari-hari biasa,
begitu bel pulang terdengar semua anak langsung berlari berhamburan
meninggalkan ruang kelas. Kali ini hening senyap. Semua seperti tersirap hantu
kolor ijo. Semua seperti tak memiliki pita suara.
Aku mengajak Michael
pulang bersama. Kami berjalan kaki sambil berencana untuk mendatangi Pak Ateng
di rumahnya. Kami bermaksud menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.
Kami sepakat untuk
mengunjunginya pada hari itu juga. Di sore harinya. Ketika kami tiba di
rumahnya, ia sedang bertelanjang dada sambil berangin-angin di teras depan.
Kami dipersilakan duduk dan menarik napas.
Otak kami sedang
merancang menyusun kata-kata pembelaan untuk disampaikan. Beliau sudah lebih
dahulu memberondong dengan nasihat yang panjang lebar. Seolah kami yang
bersalah. Kamilah pelakunya.
Namun setelah aku
jelaskan semuanya baru ia menyesal dan minta maaf. Ia berjanji untuk mengusut
tuntas pelaku sebenarnya. Tapi apa mau dikata. Sampai aku lulus dari sekolah
itu, tak pernah kuketahui siapa orang ‘kotor’ yang telah mencuci tangan dalam
‘baskom’ penderitaanku. Brengsek!
Setelah kejadian itu aku seperti tercemeti. Aku terus mengasah diri berpacu mengejar prestasi sebagai siswa terbaik. Akhirnya, melalui kerja keras dan doa Papa-Mama serta perkenanan Tuhan aku lulus. Secara akademis aku berhasil meraih nilai tertinggi di antara alumnus lainnya. Aku memperoleh beasiswa.


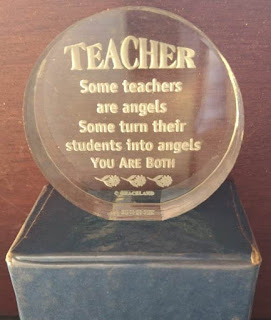
Comments
Post a Comment