GOODBYE AND SO LONG NOEKELE!

Ilustrasi dari id.pinterest.com
Kami menempati sebuah
rumah setengah tembok milik Opa di Noekele. Rumah setengah tembok itu maksudnya
sepertiga dari dinding rumah itu tembok. Sepertiga itu mulai dari fondasi ke
atas. Sisanya ditutupi dengan papan atau bebak.
Rumah itu diapit oleh
rumah keluarga Ruben Ome di sebelah Timur. Di sebelah Barat keluarga Luis Sula.
Di Selatan keluarga Felipus Muni. Dan agak jauh di sebelah Utara melintasi
sebuah got kecil terdapat rumah keluarga Daud Thao dan keluarga Filipus Tanau.
Lorrinne sekolah di SD
Negeri Besleu. Ia duduk di kelas satu walau baru berusia lima tahun. Terpaksa
ia belajar di kelas satu karena sekolah itu yang paling dekat dengan rumah. Jaraknya
sekitar kurang lebih tiga kilometer. Juga karena tidak ada TK di sana. Sewaktu di
Jakarta ia pernah belajar di TK. Jadi menurutku tidak masalah.
Istriku sibuk
mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Ya, untuk
menjadi guru. Setiap hari ia ‘mengukur’ jalan dengan rute yang sama. Yaitu dari
Noekele ke Kupang pergi pulang yang berjarak 90 kilometer.
Ia akhirnya lulus dalam
ujian itu. Hanya tidak sempat menjadi pegawai negeri di Kupang karena keburu
kembali ke Jakarta. Seminggu sebelum SK (surat keputusan) turun kami telah
berada di ibukota. Di Jakarta.
Setiap pagi selama
tinggal di Noekele aku selalu mendengar lagu rohani Ambon. Puji-pujian yang
mengalun dari balik dinding rumah Papa Ruben Ome. Tetangga di Timur rumah kami.
Dan di sore hari suara
merdu Jimmy mengalunkan lagu favoritnya: “S’lamat
Tinggal Masa Lalu.” Jimmy adalah anaknya Daud Thao. Ia keponakanku.
Suaranya terbawa angin dari atas pohon ketika ia mengumpulkan daun untuk
makanan sapi.
Ya, selamat tinggal masa
lalu. Aku sedang mencoba menggapai masa depan yang cerah. Namun apa mau dikata.
Semuanya tidak berjalan mulus seperti yang diangankan. Seperti yang kuharapkan.
Apa yang telah kukonsep
dengan rencana yang lumayan sistematis tidak berjalan dengan baik. Semua di
luar dugaan. Aku gagal. Cita-citaku menjadi petani kecil dan guru ‘besar’ pupus
kandas terbengkalai.
Selama proses perintisan
program penjaskes/olahraga di UKAW aku tidak mendapat gaji alias gratis. Seng ada kepeng. Aku hanya hidup dari
belas kasihan saudara dan orangtua. Aku malu pada diri sendiri, juga pada
istri.
Sisa tabungan di tangan
semakin lama makin terkikis. Terus menipis dan habis. Istri frustrasi. Ia tidak
tahan. Emosinya kadang kebablasan tak terkontrol. Aku praktis tidak bisa
berkonsentrasi. Kami kembali ke Jakarta.
Semua ‘harta’ kutinggalkan
kecuali pakaian di badan. Kekayaanku hanya berupa buku. Barang-barang
elektronik dan mesin tik. Peralatan makan dan dapur. Kaset dan album foto serta
beberapa potong pakaian lainnya.
Tak sanggup kubawa semua
karena tak ada ongkos. Hal yang masih kusesalkan adalah keluargaku menyingkir
menjauh satu demi satu. Padahal kami sedang dalam kebingungan. Kami dalam
keadaan frustrasi menjalani hidup di desa kecil itu.
Mereka hanya bergeming
melihat kami dalam kondisi terpuruk seperti itu. Bahkan sampai kami pulang
kembali ke Jakarta. Mereka seperti tidak memperdulikan kami. Tapi sudahlah. Semuanya
telah berakhir.
Kami mendarat lagi di
Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta pada pukul 21.00 WIB. Angka di
kalender menunjukkan tanggal tujuh November sembilan lima. Tahun sembilan lima
inilah yang kusebut sebagai tahun cerah-bersinar-benderang dan tahun
suram-kelam-mengharukan di lembaran-lembaran sebelumnya.
Di sinilah bagian suran-kelam-mengharukan itu. Aku memulai dari nol kilometer lagi. Aku harus merangkak dari anak tangga paling bawah. Aku kembali mengumpulkan tenaga untuk menyusun kembali mozaik hidup yang berserak.


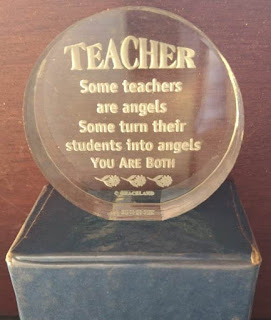
Comments
Post a Comment