BELAJAR FOTOGRAFI
Pertama kali
aku memegang dan menggunakan kamera pada tahun tujuh delapan. Kamera ini aku
pinjam dari Papa. Aku pinjam untuk memotret ‘orang besar’ dari ibukota RI. Orang
nomor satu yang mengatur kemaslahatan pendidikan Indonesia.
Aku sudah lupa
mereknya. Tetapi yang jelas kuingat adalah kamera itu semi-auto. Semi fokus.
Kamera Papa ini kecil ukurannya. Tapi bukan kamera poket. Lensanya tidak bisa
dibongkar pasang. Dia tetap seperti itu di situ sampai ajal menjemput.
Di lensanya
tertera gambar gunung artinya untuk pemandangan atau pengambilan gambar jarak
jauh. Ada gambar dua orang artinya untuk pengambilan gambar jarak sedang. Dan
ada terpampang gambar satu orang setengah badang berarti untuk jarak dekat dan close up.
Waktu itu
sekolahku, SMP Negeri II Kupang sedang kedatangan seorang tamu agung dari
Jakarta, Dr. Daoed Yoesoef. Ia berkunjung ke sekolah kami dengan kapasitas
sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia.
Maka aku meminjam
kamera Papa untuk mengabadikannya. Lumayan untuk kenang-kenangan. Tapi
gambarnya yang telah kuambil entah di mana sekarang? Mungkin telah hilang atau
dimakan rayap.
Aku tidak
membeli film. Sebab masih tersisa beberapa di dalam kamera. Karena kamera itu
adalah milik Papa, maka pastilah film yang masih ada di dalam kamera itu milik
Papa juga. Ia yang beli. Ia biasa menyisakannya untuk mengambil momen-momen
tertentu yang pantas menurut dia.
Dengan
berbekal kamera yang sudah ada isi itu aku bergaya. Aku jepret sang Menteri
dari segala sudut. Apakah ia sedang duduk, bicara atau berjalan. Semua aku
abadikan. Aku berlagak seperti seorang fotografer top atau wartawan foto yang
sangat menguasai teknik foto.
Aku berpindah
dari satu tempat ke tempat lain membidik kamera. Aku berbaur dengan juru potret
lain yang betul –betul profesional. Mereka berasal yang dari ibukota maupun
yang lokal. Semua berebut membidik demi mendapat gambar terbaik.
Tidak terasa
filmnya habis. Film yang ada dalam kamera tak bisa berputar lagi. Sementara aku
tak punya persediaan yang baru. Akhirnya aku tak lagi beraktivitas dengan
kamera. Aku hanya menyaksikan saja kegiatan yang berlangsung.
Setelah
kukembalikan kameranya, Papa bukannya memuji. Malah sebaliknya memarahiku
habis-habisan sampai tuntas. Pangkal persoalannya karena aku menghabiskan sisa
filmnya. Ampun dech boss! Sekalipun
marah, Papa tetap mencetaknya.
Apa yang
terjadi? Dari sekian banyak gambar yang aku ambil, hanya lima lembar yang jadi.
Maksudnya ada gambar, walaupun dengan wajah yang terpotong, badan dibelah dan
lain-lain. No Problem. Yang penting
ada wajah Pak Menteri yang terhormat.
Pengalaman ini
adalah yang pertama sekaligus yang terakhir. Setelah itu vakum. Aku tidak
pernah lagi menggunakan tustel, sampai aku hijrah ke Jakarta. Aku melanjutkan
pendidikan di sana. Pendidikan yang tidak ada kaitannya dengan fotografi.
Kegiatan
potret-memotret, mengintip dari balik kamera ini aku ‘tekuni’ waktu aku mampu
membeli sebuah tustel bekas. Aku membeli dengan uang pinjaman dari sekolah. Itu
aku lakukan untuk mengabadikan anakku, Lorrinne, di hari ulang tahunnya yang
pertama bulan April tahun sembilan satu.
Aku tidak
mengerti merek dan kualitas. Sama sekali buta pengetahuanku tentang foto. Baik
tentang teknik maupun mesinnya. Oleh karena itu aku datang ke toko kamera bekas
(loak) di Pasar Baru. Aku hanya sekedar lihat-lihat. Bila ada yang menarik dan
dapat disesuaikan dengan ‘ketebalan’ kocek,
kubeli.
Ternyata aku
ditawari. Penjualnya menerangkan panjang lebar tentang segala keunggulan kamera
itu. Aku hanya mengangguk kosong. Sekedar menghidupkan suasana dan biar tetap
terjalin kontak atau komunikasi dengan penjualnya. Dan juga agar aku tak
dibilang bloon. Padahal ia.
Setelah
tawar-menawar, kami sepakat. Aku berikan uangnya dan dia menyerahkan kameranya.
Mereknya: Yashica. Berlensa focus 50 mm. Tipe: FX-3 2000. Warna kameranya hitam
sempurna. Tidak besar. Sedang-sedang saja.
Sejak saat itu
aku giat belajar untuk menguasai teknik foto yang sesungguhnya. Aku membaca
majalah atau buku fotografi. Aku juga bertanya pada para professional yang aku
kenal untuk menambah pengetahuan tentang foto. Aku pun terus belajar menjiwai
kameraku.
Dari belajar
keras itu, aku dapat menghasilkan gambar-gambar apik yang bisa kupajang di rumah. Aku menjepret istri dan anak-anakku.
Aku senang memajang gambar-gambar mereka. Aku bangga kalau bisa
mengahasilgambarkan wajah-wajah mereka. Puas rasanya aku memandang dinding yang
bergelantungan potret mereka hasil jepretanku.
Aku memotret
manusia, binatang, kembang, dan pemandangan. Apa saja yang kupandang layak
untuk diabadikan. Bila artistik menurut ukuranku aku jepret. Itupun kalau ada
uang untuk membeli film dan memprosesnya setelah digambar.
Dari semua
obyek yang pernah kufoto, pemandangan dan kembang lebih menggoda dan mengusik
perhatianku. Menurutku, mereka sangat menantang daya kreativitasku. Sangat
atraktif dan indah untuk dipotret.
Padahal
menurut teori fotografi yang pernah kubaca obyek foto yang bagus bukan itu. Para
praktisi senior di dalam dan luar negeri yang sudah membuana juga mengatakan
hal yang sama.
Menurut mereka
obyek foto yang paling memiliki nilai seni dan nilai artistik tinggi adalah
wanita. Mereka mengatakan, setiap ruas dari tubuh seorang perempuan merupakan
obyek foto yang terindah.
Itu sebabnya semoga
aku memiliki cukup uang untuk bisa bergaya dengan kameraku. Sehingga aku bisa
mengambil gambar istri dan anak perempuanku. Akan aku praktikkan sampai
berhasil membuktikan teori itu.
Aku akan menguji kebenaran teori tersebut. Aku bilang ‘kalau cukup punya uang.’ Karena memang fotografi menghabiskan biaya yang besar. Ia merupakan salah satu hobi orang-orang berkantong tebal. Sementara aku sendiri orang yang berkantong tambal.


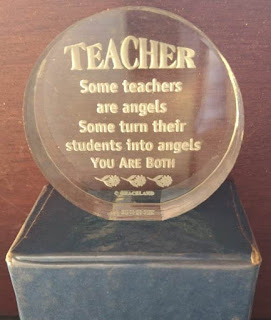
Comments
Post a Comment