DILEMA
Perkuliahan berjalan
lancar tanpa hambatan yang berarti. Lancar karena dari awal telah kuniati. Dari
kampung sudah ada tekad kuat untuk selesaikan pendidikan apapun kendalanya.
Lancar karena aku tak mau terhambat. Sebisa mungkin setiap masalah terpecahkan.
Apapun persoalannya aku
tak mau tenggelam tergilas oleh masalah. Masalah yang berhubungan dengan
ekonomi. Masalah akademik. Apa saja. Karena masalah-masalah itu akan selalu ada
dan terus menguntit dengan setia. Selama manusia itu ada, masalah akan tetap
ada. Maka aku tak mau berfokus pada persoalan tapi pemecahannya.
Secara akademis aku
tidak pandai sekali, apalagi jenius. Tapi terus terang aku rajin dan tekun. Ya,
penilaian subyektifku saja. Maksudnya aku tak mau menunda apapun yang bisa
kubereskan sekarang. Jadi setiap kegiatan yang berhubungan dengan kuliah aku
selalu kerjakan dengan baik dan maksimal. Tuntas.
Ya, seperti kuhadapi
kali ini. Kejadian yang menurutku cukup berkesan. Maka perkenankan kuceritakan
kembali kepada pembaca yang terhormat. Semoga dapat dinikmati dengan sukacita. Demikian!
Pada waktu itu adalah masa-masa ujian
semester. Mata kuliah yang akan kuhadapi adalah praktik senam. Namanya Senam
Artistik. Berarti secara fisik harus prima. Ujian akan dilaksanakan pada pukul
empatbelas. Jam dua siang.
Ijinkan aku
memberitahukan sedikit situasi kampus. Tentang budaya belajar kami yang sudah
terinternalisasi. Khususnya dalam mata kuliah praktik.
Di fakultas tempatku
menuntut ilmu, antara mata kuliah praktik dan teori adalah fifty-fifty. Seimbang. Kami benar-benar dituntut untuk tetap prima
secara fisik, mental dan intelektual. Tak jarang setelah praktik di lapangan
kami harus masuk kelas dan belajar teori kemudian praktik lagi.
Praktik yang dimaksud
seperti: Atletik, Sepakbola, Bolabasket, Bolavoli, Renang, Silat, dan masih
banyak lagi. Yang jelas hampir semua cabang olahraga; kecuali golf, ski, terjun
payung dan cabang-cabang lainnya. Karenanya kami dengan sendirinya harus prima.
Aku lebih sering menuntut memaksa diri agar tidak ketinggalan.
Aku harus serius dan berkonsentrasi
penuh agar lulus karena ini adalah ujian akhir, ujian semester. Sebab bila
sebaliknya, gagal maka aku harus mengulang lagi. Mengulang di semester yang
sama tahun mendatang. Itu berarti rugi. Rugi waktu. Rugi tenaga. Dan otomatis
rugi dana. “Aku harus lulus,” begitu tekadku kuat.
Sekali lagi harus
kuberitahu bahwa kami diberi target bila ingin lulus. Dalam semua cabang
olahraga ada target masing-masing. Bila target tidak tercapai artinya mengulang
lagi. Tidak ada toleransi. Termasuk yang sakit, apalagi yang bolos. Sudah
dipastikan mengulang. Tidak lulus.
Targetnya seperti
begini! Di antaranya. Lari seratus meter harus dua belas detik. Lompat tinggi
harus satu koma empat puluh lima meter. Senam harus menggabungkan
gerakan-gerakan yang mengandung unsur keseimbangan, kelenturan, kekuatan dan
keindahan. Begitulah.
Nah, tempat tinggalku
jauh dari kampus. Jadi kalau aku pulang rumah waktunya tidak cukup. Maka sambil
menunggu tibanya jam ujian, aku main ke tempat kos temanku. Kami biasa
memanggilnya Jimmy Montoya padahal nama aslinya Mohammad Taufik.
Ia bukan hanya teman
kuliah tapi juga adalah teman sedaerah. Kami juga adalah teman sekelas waktu di
SGO Negeri Kupang. Ia telah almarhum. Meninggal tahun sembilan empat akibat
penyakit lever berkepanjangan yang
diidapnya.
Jam makan siang tiba.
Perut harus diisi agar ada tenaga waktu ujian. Sebab sejak pagi belum sebutir
pun nasi yang masuk. Aku hanya minum teh manis. Maka aku berharap Jimmy punya
stok makanan. Paling tidak, makanan kecil atau cemilan. Ternyata tidak.
“Joy, sori nggak ada makanan. Uang, apalagi!”
Katanya lirih.
“Bagaimanapun, kita
harus makan,” balasku. Aku merogoh kantong. Menggeledah ke segala sudut celana
dan baju. Berharap ada uang ribuan terselip. Eh, benar. Dapat. Tujuh puluh lima rupian. Hanya itu. Itupun untuk
ongkos pulang yang waktu itu tarif regulernya masih lima puluh rupiah. Aku
bingung. Bimbang. Galau.
“Sekarang mana yang
harus kuprioritaskan, mana yang harus kukesampingkan?” Semua penting. Otakku
bekerja keras. “Kalau makan, pulang jalan kaki. Kalau nggak makan berarti lemas. Nggak
ada tenaga. Konsentrasi buyar. Hasilnya bisa hancur.”
Di puncak kebimbangan
yang berkecamuk di benakku kuambil uang itu. “Nih, Jim, be (saya) cuma
punya itu.” Sambil menyerahkan uang itu kulanjutkan: “Terserah Bu (bung) mau beli apa. Pokoknya katong (kita) musti makan.” Kataku dalam
logat Kupang yang kental.
Tanpa basa-basi. Bagai kilat ia menyambar uang itu dan menghilang. Sebentar kemudian ia kembali dengan sebungkus besar nasi yang dibasahi kuah dan dua potong tahu semur. Dengan lahap dan penuh ucapan syukur, kami habiskan menu istimewa itu tanpa sisa. Uennaak tenan. Sedaap!


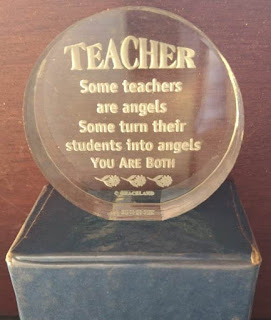
Comments
Post a Comment