TEORI versus PRAKTIK
Tadi
malam aku bertemu dan berbincang-bincang ringan dengan beberapa teman lama.
Kami bertemu secara tidak sengaja di warung makan yang ternyata adalah milik
teman kami juga. Setelah makan, kami mengahabiskan waktu sekitar hampir dua jam
atau mungkin lebih. Kami bincangkan banyak hal secara acak tak tertata.
Maksudnya bila salah satu melontarkan ide maka yang lainnya ikut menimpali urun pendapat. Ada yang pro ada yang
juga yang kontra. Beda tipis dengan acara-acara diskusi atau debat di
stasiun-stasiun televisi tanah air. Bedanya kami hanya di warung sederhana
tanpa penonton, sedangkan mereka di layar kaca ditonton banyak orang. Kadang
topik yang didiskusikan sampai pada kesimpulan. Tapi ada juga yang tidak sampai
tuntas. Dia mengambang begitu saja. Intinya adalah kami sama-sama menikmati
pertemuan dalam sukacita ketulusan.
Topiknya,
seperti tadi kubilang, beragam. Topik yang berhubungan dengan organisasi keagamaan
tempat kami berhimpun kami membahas teknis penyelenggaraan, kebijakan, dan sebagainya.
Tapi aku harus tegas bilang bahwa kami bukan bergosip. Karena aku bukan tipe pegosip,
jadi sama sekali tidak berselera untuk itu. Seandainya gosip, aku biasanya akan
meminta untuk bahas yang lain. Atau kalau mereka berkeras, maka akulah yang pamit
mundur. Jadi tidak bergosip ria. Apalagi percakapkan yang negatif. Tidak. Kami hanya
sedang menyalurkan energi berpikir antarsesama orang sisa-sisa. Apalagi covid
mengurung sekian lama, ini kesempatan saling melepas rindu. Rindu
berkongko-kongko dan rindu berbagi cerita, juga rindu berbagi ilmu.
Coronarius
dan dampaknya juga menjadi bahan bincang. Tapi bukan tentang teknis
melenyapkannya. Semua seolah kompak menyatakan keluhan dalam bertanya: “Kapan
covid ngibrit, biar kita bisa bebas
lepas seperti sedia kala?” Dan semua pun seolah memberikan jawaban yang sama
dalam nada harap yang nisbi, tak pasti: “Mungkin besok, Minggu depan atau
sebulan lagi. Dan banyak mungkin lainnya. Entah! Dia seperti tak berujung.”
Karena mengenai covid 19 tak bersambut balas yang enak, tidak menarik, maka
kami pun beralih ke topik lainnya. Sebab corona dibahas seperti apapun, situasinya tetap
tidak berubah. Jadi kami tutup pembicaraan mengenai covid dan kroni-kroninya.
Kami beralih ke lain hal.
Kali
ini tentang hobi atau aktivitas keseharian. Apa yang diminati. Apa yang
dikerjakan dengan sukarela dan berlama-lama. Teman yang punya warung mengatakan
setiap harinya di warung. Selain sebagai mata pencaharian, ini juga hobi yang
tersalur dan menghasilkan karena dasarnya kedua suami istri ini senang masak.
Dan memang masakannya enak sekali. Racikan bumbunya memberi efek ketagihan bagi
yang pernah mencicipi. Aku tak bisa menguraikan rasa seperti para juru masak
pro. Tapi aku harus bilang bahwa rasa masakannya tak kalah nikmat dengan yang ditawarkan
di rumah makan sekelas restoran. Harganya pasti terjangkau. Tapi aku tak tahu
pasti karena makananku dibayar oleh teman yang pebisnis. Dia melarangku bayar
dengan berkata dalam nada canda, yang menurutku tak melukai martabat sahabat.
Katanya: “Maaf, uang pak guru tidak laku di sini.” Lalu dia menyelesaikan
transaksi dengan teman pemilik warung sesaat kami akan berpisah.
Teman
yang pebisnis mempunyai hobi menyanyi dan bermusik. Maka dia beberkan
kesehariannya selama masa karantina terpaksa ini. Jabarnya: “Saya belajar dari
media tentang bagaimana main gitar. Khususnya yang bergendre jazz. Dan belajar
lagu-lagunya. Jazz maksud saya.” Wow,
keren. Pikirku. Dan memang teori musik jazz yang didapatnya dari pembelajaran
melalui media-media itu menakjubkan. Dia menerangkan banyak kepada kami tapi
aku tidak terlalu paham. Dan kelihatannya begitu juga dengan teman pemilik warung. Aku
memang bisa memetik gitar. Tapi hanya sekadar pelipur diri. Aku kurang memahami
teori musik secara mendalam, apalagi jazz. Karenanya, kami, aku dan pemilik
warung sama-sama bias kurang antusias dalam menanggapi. Kami – yang tak
berpengetahuan ini – seperti sedang mengikuti kuliah umum dengan pakar musik
internasional. Kami hanya mampu mendengarkan bengong
dengan pikiran tong kosong.
Aku
sendiri menceritakan keseharianku selama masa kepengurungan hanya dengan
membaca dan menulis. Membaca dari perbendaharaan buku yang cuma seberapa yang
kupunya. Dan menulis apa yang mendesak ingin dituangkan. Atau memaksabiarkan jari-jemariku
menari-nari di atas tuts laptop walau tanpa ide. Nanti di saat kata demi kata kutulis
baru ide bermunculan datang menghampiri menawarkan diri untuk diurai. Atau kalau
mati langkah merangkai kata, aku berhenti beberapa jenak. Keluar dan menyiram
tanaman sebagai penyeling sekaligus hiburan yang menyegarkan. Tanaman yang kusiram
adalah: Cabe, tomat, dan beberapa pohon buah yang masih membutuhkan asupan air
sebelum mereka mampu mencari air sendiri.
Karena
penasaran tentang teori musik memusingkan itu, aku minta dia contohkan secara praktik sederhana ke dalam chord.
Maksudnya biar aku bisa mendapat sedikit keterampilan dari pertemuan sederhana
ini. Ia pun menunjukkannya. Yaitu menerjemahkan teori-teori tadi langsung
dengan gitar yang kebetulan ada. Gitar milik anak teman pemilik warung yang
biasa ia mainkan kala menemani Papa-Mamanya. Sayangnya, kemampuan teroretis
yang dimiliki tidak berbanding lurus – atau tidak linear, kata para akademisi –
dengan kemampuan praktisnya. Karenanya dia memberiku gitar itu untuk memainkan chord mengikuti petunjuk teoretis yang
disampaikannya. Lumayan. Selama ini aku hanya mengikuti cara bermain orang lain
apa adanya. Istilahku, bermain secara kampung tanpa teori. Sekarang aku dapat
sesuatu. Aku bisa menerjemahkan teori yang jelimet ke dalam nada-nada praktis
berkat kesabaran dan tuntunan temanku yang fasih teori. Kami pun melantunkan
beberapa lagu penenang jiwa sebelum berpisah.
Dari
pengalaman ini aku bermonolog sepanjang jalan pulang. Kubiarkan nalar dan
naluriku bertanya jawab.
Kata nalarku: “Jadi mana lebih baik, teori atau praktik? Mana yang seharusnya lebih
dahulu dikuasai antara teori dan praktik?”
Lalu
naluriku menjawab: “Bukan mana lebih baik atau mana yang lebih dahulu. Tapi
harus saling mengisi, saling menopang!” Dengan tidak sabaran nalarku merespon.
“Maksudnya?”
“Ya.
Kalau misalnya teori lebih dahulu dikuasai, maka harus dibarengi dengan latihan
keras untuk mewujudnyatakannya dalam bentuk praktik praktis. Atau kalau lebih
dahulu bisa mempraktikkan, maka harus berusaha memahami teorinya agar tidak
ngawur. Sebab teori dihasilkan dari pengamatan cermat atas tindakan-tindakan
praktik lalu diuraibahasakan. Kemudian diujicobakan kembali dalam bentuk
praktik. Dan keterampilan-keterampilan memukau yang ditampilkan para maestro
berasal dari latihan yang berulang-ulang dari teori yang diperoleh.”
“Sederhananya?”
“Kalau
sudah punya teori yang mumpuni, berlatihlah sesuai teori yang dipunyai supaya
terampil. Atau kalau sudah terampil, belajarlah teorinya agar semakin kaya dan
tidak sembarang.”
Belum
juga nalarku mau berargumen lebih lanjut dengan naluriku, aku sudah sampai di
rumah. Dan karena sudah lelah aku langsung beristirahat. Mereka pun ikut terlelap.
Yolis Y. A. Djami (Tilong-Kupang, NTT)
Kamis, 30 April 2020 (11.04 wita)


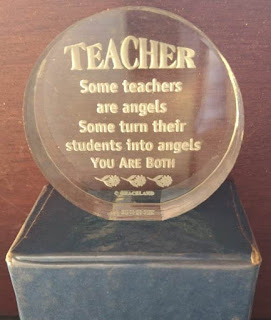
Comments
Post a Comment